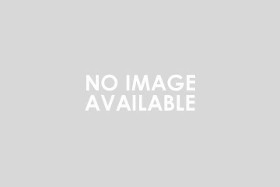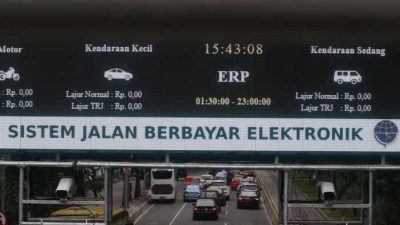Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2025 yang berisi tentang Rencana Aksi (.
Road Map
Transisi Energi di Sektor Kelistrikan (Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025). Bagian penting dari regulasi ini meliputi kriteria untuk pensiun awal pembangkit listrik berbahan bakar batu bara (PLTBG), yang mencakup sepuluh parameter dan menetapkan bobotnya menggunakan teknik hibrida.
Analytical Hierarchy Process
(AHP) serta pendapat pakar dari beberapa disiplin ilmu.
Indikator awal merupakan kemampuan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan beban sebesar 4,4%, disusul oleh umur pembangkit yang memiliki bobot sama yaitu 4,4%. Kemudian ada indikator utilitas atau penggunaan, yang mana bagian ini belum Anda lengkapi selengkapnya.
capacity factor
PLTU mendapat pembobotan sebanyak 5,2%. Kemudian, tersedianya dukungan teknologi diberikan beban 6,4%, sedangkan emisi gas rumah kaca dari PLTU dibebani dengan persentase 9,3%.
Secara ekonomis, kontribusi pertambahan nilai ekonomi mencapai 9,8% dari total, sementara itu, penunjang pembiayaan memperoleh beban tertinggi sebesar 27,1%. Selanjutnya, stabilitas jaringan listrik menempati posisi 13%, disusul oleh akibat kenaikan dalam biaya dasar pengadaan yang memberikan dampak pada harga energi listrik sekitar 10,3%, serta implementasi aspek tersebut juga dipertimbangkan.
just energy transition
sebesar 10,1%.
Akan tetapi, setelah melihat dengan cermat strukturnya serta beban kriterianya, beberapa pertanyaan signifikan timbul. Apakah pendekatan ini sungguh-sungguh menjunjung tinggi hak lingkungan dan kesetaraan? Atau malah hanya fokus pada aspek-aspek ekonomi dan teknikal saja?
- Emitasi Gas Karbon di Sektor Energi dan Industri Dunia Naik Pada Tahun 2024
- Bursa Karbon Sebagai Bagian dari Rencana PLN untuk Proses Tranformasi Enerji
- Pemadaman Massal Berlangsung Lama di Spanyol: Apakah Energi Terbarukan Terganggu?
Indikator Bias Lingkungan
Dalam sepuluh standar yang dirumuskan di Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025, beban terberat dialokasikan untuk adanya dukungan pembiayaan, yaitu mencapai 27,1%. Ini mengindikasikan bahwa aspek keandalan ekonomis merupakan faktor paling dominan dalam penetapan pembangkit listrik tenaga uap mana saja yang harus dimundurkan masa pakainya.
Di samping itu, penunjuk lingkungan seperti emisi gas rumah kaca hanya mendapat beban sebesar 9,3%, nilai yang cukup kecil mengingat tingkat urgensi mereka. Sebenarnya, elemen ini haruslah menjadi dasar utama dalam merancang rangkaian perubahan energi menuju keberlanjutan.
Emiten gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap bukan saja memberikan kontribusi signifikan pada masalah perubahan iklim dunia, melainkan juga menciptakan dampak lingkungan lain seperti polusi udara, peningkatan risiko penyakit bagi manusia, rusaknya ekosistem alami, serta merugikan mutu kehidupan untuk banyak generasi mendatang. Pengaruh buruk tersebut bersifat luas dan abadi, mengubah berbagai aspek mulai dari faktor sosial sampai stabilitas iklim secara keseluruhan.
Secara umum, apabila tingkat polusi udara naik, maka biaya kesehatan juga akan meroket. Akan tetapi, hal tersebut tidak tercermin dengan baik dalam metode penimbangan yang dipakai karena terhalangi oleh pendekatan teknokratik dan finansial.
Lebih lanjut, indikator
just energy transition
hanya mendapatkan bobot 10,1%. Namun, sayangnya, tidak tersedia penjelasan rinci mengenai ruang lingkup maupun parameter penilaiannya. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan, membuka peluang terjadinya multitafsir oleh pemerintah.
Oleh karena itu, model ini cenderung memfokuskan perhatiannya pada kesesuaian pembiayaan serta sisi teknis daripada kepentingan lingkungan. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang diidentifikasi sebagai salah satu kontributor utama gas rumah kaca dan pemicu polusi lokal signifikan, justru ditetapkan sebagai elemen yang bisa “beroperasi lebih lama” selama tetap dipandang patut dari segi finansialnya.
Hal ini tentunya bertolak belakang dengan janji Indonesia untuk memperkecil emisi serta pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, dimana ia menegaskan bahwa pembangkit listrik tenaga uap batubara akan berakhir dalam jangka waktu 15 tahun ke depan.
Minimnya Perspektif Publik
Pada tahap pembentukan standar, sepertinya belum ada kontribusi signifikan dari organisasi masyarakat sipil, grup yang terpengaruh, serta pakar akademik. Ini menyebabkan struktur perubahan energi masih diatur oleh para elit pengambil keputusan, daripada didasarkan pada permintaan nyata akan berbagai efek langsung operasional PLTU yang sudah sering kali menciptakan masalah.
Kurangnya partisipasi dari pemain utama, tentunya bertolak belakang dengan pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Pasal tersebut secara tegas memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait perencanaan penyusunan kebijakan umum, rancangan kebijakan publik, dan juga mekanisme pengambilan putusan dalam urusan publik bersama alasan-alasannya.
Di samping itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Proses Legislasi juga menekankan asas partisipasi yang substantif, di mana warga negara memiliki hak untuk dipertimbangkan.
right to be heard
), kesempatan untuk diperhitungkan (
right to be considered
), dan saya untuk mendapat klarifikasi (
right to be explained
).
Tinjau Ulang Indikator
Agar transisi energi menjadi lebih adil, pemerintah harus mengkaji kembali strategi yang terlalu fokus pada bidang ekonomi. Minimal ada empat unsur penting yang sebaiknya ditingkatkan dalam penilaian untuk pensiun dini dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Pertama,
Indikator mutu lingkungan, misalnya informasi tentang pencemaran udara, air, serta pengaruhnya pada kesejahteraan penduduk.
Kedua,
kerentanan sosial-ekologis
,
terutama di daerah yang berpenduduk tinggi dan memiliki ekosistem yang rapuh.
Ketiga,
tingkat keterlibatan masyarakat, sebagian dalam rangka penyusunan kebijakan.
Keempat,
dampak jangka panjang
,
Termasuk dampak pada aspek kesehatan, perekonomian setempat, serta kemampuan mendukung lingkungan. Dengan menyertakan dimensi tambahan ini, tahap evaluasi bukan saja semakin luwes dalam cakupannya, namun juga jadi lebih bijaksana untuk kelompok masyarakat di masa depan.
Transisi energi perlu diartikan sebagai kesempatan untuk merevisi sistem energi nasional yang bersifat eksploitasi dan tak lestari. Jika standar dan cara pengukuran cenderung mendukung pendekatan proyek serta ragu-ragu dalam melangkah keluar dari jeratan dependensi ekonomi ekstraktif dan dominansi kapitalisme, maka rute menuju transisi ini bisa saja menjadi alasan semata bagi pelestarian pembangkit listrik tenaga uap batubara yang mestinya sudah saatnya pensiun.