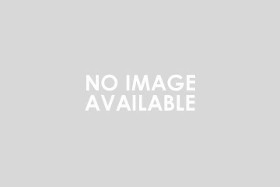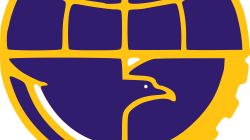Konservasi yang Tidak Melibatkan Rakyat
Di sebuah pagi di Ngkiong, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mikael Ane duduk memandang ladang yang telah diwariskan oleh keluarganya selama berabad-abad. Di sanalah ia menanam jagung dan melakukan aktivitas pertanian dengan cara adat, yang melibatkan penghormatan kepada leluhur. Namun bagi pemerintah, tanah itu adalah kawasan konservasi. Tanpa izin negara, keberadaannya di sana dianggap melanggar hukum. Ia sempat dipenjara—bukan karena merusak hutan, tapi karena mencintai hutan dengan cara yang berbeda dari pemerintah.
Kisah Mikael adalah salah satu dari banyak cerita yang muncul setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) disahkan pada Juli 2024. Alih-alih memperbaiki warisan konservasi yang eksklusif dari UU Nomor 5 Tahun 1990, regulasi baru ini justru mengukuhkan ketimpangan: hutan harus steril, manusia dianggap gangguan, dan suara masyarakat adat tetap dipinggirkan.
Bersama tiga organisasi lain—AMAN, WALHI, dan KIARA—Mikael mengajukan uji formil undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi pada September 2024. Mereka tidak hanya menyoal isi undang-undang tersebut, tetapi juga bagaimana undang-undang ini dibentuk: tanpa partisipasi nyata, tanpa keterbukaan, dan tanpa kejelasan arah. Sebuah undang-undang yang lahir dengan tergesa dan bias, padahal dampaknya bisa sangat panjang.
Konservasi: Dari Rakyat, Untuk Siapa?
Dalam buku-buku resmi Indonesia sering disebut bangga memiliki luas hutan yang masuk lima besar di dunia. Namun jarang disebut bahwa di balik rimbunnya pepohonan itu, ada puluhan sampai ratusan ribu manusia dan komunitas adat yang hidup dan menjaga kawasan tersebut. Mereka menyebut hutan sebagai ibu, bukan sekadar sumber daya.
Data dari Working Group ICCAs Indonesia (WGII) mencatat lebih dari 600 ribu hektare wilayah adat telah didokumentasikan sebagai kawasan konservasi berbasis komunitas. Di sana, masyarakat adat menjalankan konservasi yang menyatu dengan ritual, hukum adat, dan keseharian. Menariknya, 64% dari wilayah adat ini tumpang tindih dengan kawasan konservasi versi negara.
Namun dalam UU KSDAHE, masyarakat adat nyaris tak disebut. Tak ada satupun pasal yang mengakui mereka sebagai pelaku utama konservasi. Bahkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIK)—yang seharusnya menjadi dasar pelibatan komunitas dalam konservasi—tidak tercantum. Karena itu, ketika konservasi diperluas ke kawasan lindung, hutan produksi, hingga areal penggunaan lain, warga adat tak diberi ruang untuk menyatakan setuju atau menolak.
Proses Lahirnya UU KSDAHE yang Membingungkan
Proses lahirnya UU KSDAHE pun menyisakan banyak tanya. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah sendiri mengakui bahwa dari 20 kali rapat pembahasan RUU, hanya dua kali yang dilakukan secara terbuka. Selebihnya tertutup. Sebuah pengakuan langka yang justru memperkuat dugaan adanya cacat formil.
Di balik pintu tertutup itu, suara masyarakat adat seakan-akan hanya menjadi pelengkap. Pak Putu, satu-satunya wakil masyarakat adat yang sempat diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Senayan, menyebut partisipasinya hanya simbolik. Ia datang tanpa dibekali naskah akademik, tanpa draf RUU. Ia hanya diminta bicara, tanpa jaminan didengar.
Artinya, negara tidak pernah sungguh-sungguh ingin melibatkan mereka yang paling terdampak. UU ini lahir bukan dari ruang dengar, tapi dari ruang gelap—di mana suara rakyat dikaburkan oleh logika birokrasi dan kepentingan ekonomi.
Ancaman Terhadap Ruang Hidup Masyarakat Adat
Lebih mengkhawatirkan lagi, UU ini justru membuka jalan luas bagi eksploitasi kawasan konservasi. Dalam pasal-pasalnya, terdapat ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan ekosistem: karbon, geothermal, dan wisata konservasi. Nama-nama ini terdengar hijau, tapi sering kali berarti satu hal: izin bagi korporasi masuk ke hutan, tanpa harus berhadapan dengan warga adat.
Jika kawasan itu dianggap steril dari penduduk—sebagaimana UU ini asumsikan—maka perizinan akan menjadi lebih mudah. Maka tak heran jika masyarakat adat melihat ini sebagai ancaman baru terhadap ruang hidup mereka.
Data WGII juga menunjukkan bahwa 49% dari areal yang disebut “preservasi” dalam UU ini tumpang tindih dengan wilayah adat. Artinya, ada potensi penggusuran besar-besaran atas nama konservasi. Ironis, karena warga yang selama ini menjaga hutan malah disingkirkan demi proyek yang membungkus diri dengan jargon pelestarian.
Negara terus mengklaim kawasan hutan secara sepihak. Hingga 2024, sekitar 106 juta hektare disebut sebagai kawasan hutan negara. Dalam praktiknya, banyak wilayah adat yang secara administratif di garis sebagai kawasan ini—tanpa konsultasi, tanpa berita acara tata batas seperti diwajibkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45.
Anomali yang selanjutnya terjadi adalah, biasanya rata-rata penetapan kawasan hutan oleh pemerintah itu hanya 500 ribu hektare per tahunnya. Yang mengejutkan, pada 2022 mencatat lonjakan penetapan kawasan hutan hingga 10 juta hektare, naik 20 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Apa dasarnya? Tak pernah benar-benar jelas. Namun satu yang pasti, setiap klaim negara atas tanah, berarti pengingkaran atas hak masyarakat adat.
Mahkamah, Jangan Biasakan yang Salah
UU KSDAHE adalah satu dari sekian regulasi yang menunjukkan wajah konservasi yang eksklusif dan otoriter. Yang disayangkan, Mahkamah Konstitusi pun hanya memberi sedikit ruang untuk pemohon membuktikan argumentasi mereka. Hanya dua saksi dan dua ahli yang diizinkan hadir secara langsung, dengan waktu persiapan seminggu. Padahal uji formil seharusnya menjadi cara rakyat menuntut keterbukaan dari proses legislasi.
Salah satu hakim Mahkamah bahkan mengungkap keprihatinan bahwa pembentukan undang-undang kini berubah wajah: “Dulu semua sidang terbuka kecuali disepakati tertutup. Sekarang justru sebaliknya: semua tertutup kecuali disetujui untuk terbuka.” Sebuah pembalikan nilai yang berbahaya bagi demokrasi.
Jika Mahkamah –yang akan membacakan putusan pada Kamis, 17 Juli– tidak membatalkan UU ini, maka preseden akan terbentuk: bahwa proses yang tidak inklusif, tidak transparan, dan tidak melibatkan warga yang paling terdampak pun bisa dilegitimasi sebagai sah.
Konservasi seharusnya menjadi cerita tentang merawat, bukan menguasai. Tentang kepercayaan kepada mereka yang hidup selaras dengan alam, bukan kecurigaan yang melahirkan kriminalisasi.
UU KSDAHE, dalam bentuknya sekarang, gagal mencerminkan hal itu. Ia tak sekadar cacat secara prosedur, tapi juga cacat dalam jiwa. Ia tak menjadikan masyarakat adat sebagai bagian dari solusi, justru memposisikan mereka sebagai ancaman.
Sudah saatnya kita balik arah. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat harus menjadi landasan dari setiap kebijakan lingkungan. Untuk itu, RUU Masyarakat Adat tak bisa lagi ditunda. Tanpa payung hukum yang jelas, warga seperti Mikael akan terus menjadi korban konservasi yang membungkam. Ini celaka, sebab hutan tak akan lestari jika penjaganya terus diusir.