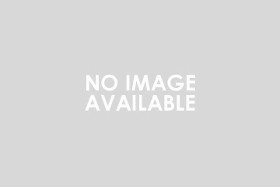Jakarta: Kota yang Terjebak dalam Anomie Ekologis
Jakarta, kota megapolitan yang tak pernah tidur. Kota yang penuh dengan harapan, ambisi, dan mimpi. Namun, ketika langit muram menumpahkan hujan dari cakrawala, kota ini berubah menjadi ruang nestapa. Jalan-jalan menjadi sungai, rumah-rumah tenggelam, dan suara pompa air menandingi deru sirene ambulans.
Di balik derasnya banjir yang melanda DKI Jakarta setiap musim penghujan, tersembunyi luka sosial yang tak kunjung sembuh. Banjir bukan hanya sekadar air yang meluap dari sungai, tetapi ia adalah cermin dari ketimpangan, ketidakadilan ruang, dan kegagalan peradaban kota dalam menata harmoni antara manusia dan alam.
Banjir di Jakarta bukan sekadar bencana alam. Ia adalah bencana sosial yang lahir dari keserakahan dan pengabaian. Beton telah menggantikan tanah resapan. Mal, apartemen, dan gedung pencakar langit menjulang menggusur rawa dan sawah. Sungai-sungai yang dahulu berkelok alami kini dicekik oleh tanggul dan betonisasi. Setiap jengkal ruang yang semula menjadi penyangga ekologis, telah dijadikan komoditas. Kota telah memunggungi alam, dan kini alam menuntut balas melalui banjir.
Jakarta dalam Perkembangan yang Terjebak dalam Anomie Ekologis
Jakarta dalam perkembangannya selalu terjebak dalam anomie ekologis. Nilai-nilai keseimbangan dengan lingkungan digantikan dengan obsesi pertumbuhan ekonomi. Dalam iklim seperti ini, alam bukan lagi sesuatu yang dihormati, melainkan ditaklukkan dan diperjualbelikan.
Banjir menjadi ancaman tahunan yang tak kunjung terselesaikan meski berbagai solusi teknokratis telah dicoba. Namun, persoalan banjir tidak bisa semata-mata dipahami sebagai masalah infrastruktur atau curah hujan ekstrem. Dalam konteks kajian sosiologis, khususnya melalui lensa “ekosipasi” yang digagas sosiolog Robertus Robet, banjir di Jakarta mencerminkan krisis ekologis yang memiliki akar dalam relasi kuasa, ketimpangan sosial, dan perampasan ruang hidup.
Ekosipasi: Kritik terhadap Pandangan Ekologis yang Reduktif
Istilah ekosipasi merupakan sintesis antara ekologi dan emansipasi, yang ditekankan oleh Robertus Robet untuk mengkritisi cara pandang ekologis yang reduktif dan terlepas dari struktur sosial. Robet menekankan bahwa krisis ekologi adalah hasil dari relasi produksi kapitalistik dan ketimpangan sosial, bukan sekadar dampak dari perilaku individual atau ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, ekosipasi mengajak kita untuk memandang perjuangan ekologis sebagai perjuangan kelas dan keadilan ruang.
Dalam perspektif ekosipasi, banjir di Jakarta bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana sosial-ekologis. Banjir terjadi karena struktur tata kota yang timpang, alih fungsi lahan yang tak terkendali, dan kebijakan pembangunan yang lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi elite ketimbang kebutuhan ekologis warga.
Ruang Hijau Terpinggirkan oleh Pembangunan Elite
Ruang hijau terus terpinggirkan oleh pembangunan hunian elite, pusat perbelanjaan, dan proyek reklamasi. Saluran air menyempit karena permukiman warga miskin yang terpaksa tinggal di bantaran sungai, bukan karena pilihan, tetapi karena keterdesakan ekonomi dan penggusuran dari wilayah yang lebih layak.
Menurut Robet, inilah bentuk dari perampasan ruang ekologis oleh struktur kuasa dan modal. Ketika ruang hidup di kota semakin dikomodifikasi, maka kelompok miskin kota yang paling terdampak. Warga tidak hanya kehilangan akses atas ruang yang sehat, tetapi juga terus-menerus menjadi korban dari bencana ekologis buatan manusia.
Pemerintah dan Kapitalisme Urban
Kebijakan tata kota DKI Jakarta masih cenderung elitis dan top-down. Proyek-proyek seperti normalisasi sungai, tanggul laut raksasa, atau pembangunan giant sea wall sering kali tidak melibatkan partisipasi warga yang terdampak langsung. Dalam semangat ekosipasi, bentuk pembangunan seperti ini sebagai bagian dari kekerasan struktural, karena meminggirkan warga miskin dari hak atas kota, sementara memfasilitasi investasi dan spekulasi properti oleh kelas atas.
Kekerasan itu hadir dalam bentuk penggusuran paksa, kriminalisasi warga bantaran sungai, hingga hilangnya akses warga terhadap sumber air bersih dan lingkungan sehat. Di sisi lain, kebijakan seperti reklamasi pantai utara Jakarta justru menambah beban ekologi kota dan memperparah banjir akibat penurunan muka tanah dan hilangnya daerah resapan.
Emansipasi Ekologis: Jalan Keluar?
Solusi atas banjir Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan teknis, tetapi juga harus menyasar pada transformasi struktur sosial dan politik ruang. Dalam kerangka ekosipasi, maka perlu mendorong bentuk-bentuk perlawanan warga terhadap perampasan ruang hidup sebagai bagian dari perjuangan ekologis. Komunitas-komunitas yang mempertahankan ruang hijau, kelompok advokasi lingkungan yang menolak reklamasi, serta solidaritas warga dalam menghadapi bencana menjadi benih dari gerakan ekosipatif.
Pemerintah kota seharusnya mengadopsi pendekatan partisipatif dan inklusif dalam merumuskan kebijakan tata kota. Keberlanjutan ekologis tidak bisa dicapai tanpa keadilan sosial. Dengan demikian, penanganan banjir seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuatan tanggul, tetapi juga pada pemulihan hak warga atas ruang hidup yang layak.
Melalui kerangka ekosipasi, kita diingatkan bahwa krisis ekologis seperti banjir di Jakarta tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa dan ketimpangan sosial yang melekat dalam pembangunan kota. Maka, untuk mengatasi banjir secara berkelanjutan, dibutuhkan lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Dalam hal ini diperlukan keberanian politik untuk mendistribusikan ruang dan sumber daya secara adil. Ekosipasi bukan hanya tentang menyelamatkan lingkungan, tetapi juga tentang membebaskan manusia dari ketertindasan yang berlangsung atas nama pembangunan.