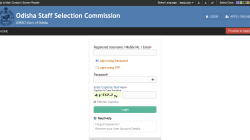Saya selalu penasaran tentang bagaimana para pejabat negara melatih empati mereka ditengah fasilitas yang super komplit dan super megah? Orang miskin yang hanya bisa menggabungkan breakfast, lunch, dan dinner dalam satu waktu secara bersamaan akan sadar betapa rasa lapar membuat tubuh mereka menderita. Ini bukan fancy lifestyle fasting yang biasa dilakukan oleh orang-orang untuk memicu autofagi-detoksifikasi & regenerasi sel tubuh yg rusak secara alami-. Sederhana, kaga ada duit le’. Pun dengan orang-orang yang selalu terjebak macet di jalan. Apakah karena mereka antusias melihat kendaraan menumpuk? Bukan pengendara prioritas dilarang mengatur lalu lintas. Dikira yang sibuk cuma plat merah kali.
Bagiamana dengan para pengendara roda dua? Jangan ditanya, debu, kotoran, bau knalpot, semburan panas mesin mobil, sengatan sinar ultraviolet, dan suara bising klakson adalah sebagian dari romantika jalanan. Masih mending punya kendaraan, bagaimana dengan pengguna transportasi umum? Harus bangun lebih pagi, harus jalan ke terminal, harus siap desak-desakan, dan pastinya harus waspada copet dan pelecehan karena tidak ada pengawal yang mengawasi. Lalu, bagaimana dengan pejalan kaki? Mungkin itu upaya mereka untuk mengurangi lingkar celana biar tidak cepat meninggal. Mereka bisa saja punya kendaraan atau naik transportasi umum, tapi kan sehat itu pilihan. Sama seperti pilihan para pejabat, apakah dengan menikmati uang rakyat melalui fasilitas yang serba ada itu akan melahirkan pamrih atau justru sebaliknya, lupa bagaimana cara berempati?
Ketika kemapanan sosial dan ekonomi membuat mereka tidak lagi merasakan ‘penderitaan jalanan’, lantas bagaimana mereka tahu bahwa orang lain sedang menderita? Sementara mereka selalu kenyang dengan makanan apapun, dimanapun, dengan harga berapapun, bagaimana cara mereka menggambarkan kondisi kelaparan? Tidak heran mengapa para pejabat kita belakangan ini seringkali mengeluarkan statement nirempati. Rasa iba, simpatik, dan afeksi memang bisa menyusut seiring kesejahteraan seseorang. Ruang pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang kurang representatif cenderung abai terhadap penderitaan rakyat. Salah satu sinyal kesenjangan perspektif terjadi ketika kericuhan peserta job fair dianggap sebagai sebuah animo.
Berakit ke Hulu, Tak Pernah Berenang di Tepian
Mari kita berbicara tentang angka sebagai sebuah realita. Data BPS menyebutkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 sebanyak 7,28 juta orang. IMF memproyeksikan tingkat pengangguran di Indonesia akan naik menjadi 5% menobatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN dan runner-up di kawasan Asia setelah China. World Economic Outlook edisi April 2025 memperkirakan angka pengangguran di Indonesia akan naik menjadi 5,1% pada 2026 mendatang. Apakah kita akan menyalip China yang konsisten di angka 5,1%? Tentu saja tidak, bukannya akan terbuka 19 juta lapangan kerja sesuai janji Wapres Gibran? Anggap saja janji itu ibarat kredit kendaraan, urusan akan dilunasi atau tidak itu menjadi hak nasabah. Tapi ingat, debt collector wajib mengingatkan. Makanya, aspirasi anak muda didengarkan dan sudahi mentalitas sok menggurui. Demo di jalan jangan dianggap remeh dan tidak penting. Membludaknya antrian pencari kerja jangan diglorifikasi sebagai semangat juang para anak muda. Giliran ngopi untuk menenangkan jiwa dan batin dibilang ngabisin duit, padahal baru saja jatuh dari parit akibat berdesakan dengan pelamar lainnya.
Responsibilization-menjadi praktik umum dalam sistem neoliberal dimana tanggung jawab negara dialihkan ke warga. Pengangguran banyak bukan karena jumlah lowongan kerja yang tersedia sedikit, melainkan para pencari kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri -skills mismatch-. Narasi ini menempatkan pencari kerja sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab atas nasib nahas karir mereka dan mengabaikan faktor struktural kompleks antara kebijakan pemerintah, peran pendidikan dan keterlibatan dunia usaha. Di Jepang, 98% lulusan Maret 2025 telah terserap dunia kerja per 1 April 2025. Gimana dengan Indonesia? Duh, jangan ditanya. Mahasiswa disibukkan dengan IPK, perusahaan semrawut cari pengalaman, dan pemerintah hobi pasang banner program tanpa menyentuh akar persoalan. Jumlah pengangguran di Indonesia didominasi lulusan SMK yang notabene-nya adalah program siap kerja. Bahkan para siswa disuruh mencari tempat PKL sendiri tanpa bantuan sekolah. “Yang penting ada sertifikat PKL, katanya,” pengakuan seorang siswa.
Proses penciptaan kerja dalam ekositem ketenagakerjaan di Jepang sebenarnya bisa saja diadopsi di Indonesia. Pertama, perbaiki sistem vokasi. Jangan ngomong doang daya serapnya cepat dipasaran dan paling siap kerja tapi tidak menjalin kerja sama dengan industri. Dunia usaha harus terbiasa melatih alih-alih sekedar menyaring. Kedua, benahi sistem job matching dikampus. No campus left behind, hindari eksklusivitas dan privilese top ten university. Bukan soal kualitas, tapi prinsip terbaik dalam sistem perekrutan kerja harus bersifat adil dan setara. Entah kenapa perengkingan acapkali menyabotase kepercayaan diri dari para lulusan kampus tak ternama. Padahal bisa jadi ada mahasiswa hidden gem loh?
Kampus juga jangan masa bodoh dan membiarkan para lulusannya berjuang sendiri. Giliran punya karir cemerlang aja baru nama kita masuk media kampus atau jadi model brosur penerimaan mahasiswa baru. Ketiga, encouraging us. Anak muda paham kok kompleksitas dunia saat ini, pentingnya re-skilling dan up-skilling, disrupsi teknologi, dan invasi kecerdasan buatan dalam bursa ketenagakerjaan. Pemerintah sebaiknya perbanyak lembaga pelatihan dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jangan sampai udah capek-capek ikut training ternyata tidak sesuai dengan kemauan industri. Dan yang terpenting adalah empati. Beban generasi sekarang tidak seberat generasi sebelumnya. Isu anak muda di era sekarang tidak sebanyak pendahulunya. Mental mereka sudah rusak karena tak kunjung dapat kerja, jangan berikan komentar yang merendahkan seperti “kamu kurang bekerja keras” “kamu kurang bersyukur” Buat kompetisinya jujur dan adil, hidupkan meritokrasi, dan stop blamming the victim dari persoalan yang sebetulnya bersifat sistemik.
‘Politik Bertahan Hidup Ala Anak Muda’
“Kalau milih-milih kerja ngga bisa makan.”
“Keluraga tidak masalah saya jadi sopir. Tapi saya pribadi merasa sayang, karena perjuangan menempuh pendidikan sarjana susah, menghabisakan waktu dibiaya.”
“Sekarang ini cari pekerjaan sulit, jadi mau enggak mau ya harus disyukuri.”
Begitulah pengakuan anak muda kita seperti yang saya kutip dari portal berita bbc. Optimisme Indonesia cerah kian runtuh, nasib anak muda kian mencemaskan, harapan kepada pemerintah kian luruh, pesimisme mulai ber-eskalasi, dan gangguan kesehatan mental kian merebak. Kita dipaksa bersyukur dalam sebuah rekayasa takdir, realitas diolah menjadi sebuah harapan, dan pada akhirnya nasib tergadai demi uang. Dalam ‘politik bertahan hidup’ ketidakjelasan nasib di masa depan dianggap sebagai hal yang lumrah, termasuk pekerjaan. Fenomena ‘Kabur aja dulu’ adalah sinyal bahwa kita sedang berada dalam mode politic of survival (politik bertahan hidup).