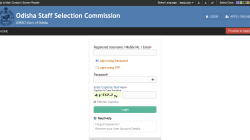Julianda Boang Manalu SH MH
, Pemerhati sosial politik Aceh, dan kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Subulussalam
DALAM
riuhnya panggung politik nasional, ada sebuah peristiwa sunyi yang luput dari perhatian banyak pihak—sebuah tragedi administratif yang menghantam marwah Aceh sebagai daerah berdaulat dengan sejarah dan identitasnya sendiri. Empat pulau kecil yang sejak lama menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—telah hilang dari peta Aceh.
Mereka bukan hanyut oleh tsunami, bukan pula menghilang karena abrasi, melainkan hilang dari dokumen negara akibat keputusan administratif pemerintah pusat. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan bahwa keempat pulau tersebut kini berada di bawah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Satu keputusan, empat pulau melayang.
Bagi sebagian pihak di Jakarta, mungkin ini hanya soal koordinat dan garis batas. Namun bagi Aceh, ini menyangkut harga diri. Ini tentang marwah—nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar batas administrasi.
Bukan sekadar pulau
Pulau kecil kerap dianggap remeh. Ukurannya yang kecil sering kali membuatnya disepelekan dalam kebijakan pembangunan dan perencanaan wilayah. Namun sesungguhnya, dalam hukum laut internasional—terutama UNCLOS 1982—pulau, sekecil apa pun, memiliki nilai strategis yang luar biasa. Ia bisa menentukan batas laut teritorial, zona tambahan, bahkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara.
Indonesia adalah negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, pulau-pulau kecil adalah fondasi dari keutuhan wilayah kedaulatan kita. Hilangnya satu pulau bukan hanya berarti kehilangan satu daratan, melainkan kehilangan ribuan kilometer persegi laut dan potensi ekonomi di sekitarnya. Dengan kata lain, pulau kecil adalah aset geopolitik. Ia bisa menjadi titik pantau militer, pos pengawasan laut, lokasi logistik pertahanan, atau sumber daya alam masa depan—baik dari sektor perikanan, energi laut, maupun pariwisata.
Letak geografis Aceh sangat strategis. Di sebelah barat, Aceh menghadap langsung Samudra Hindia—jalur pelayaran internasional yang dilintasi kapal-kapal dagang dari Afrika, Timur Tengah, hingga Asia Timur. Di sebelah timur, Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, yang disebut-sebut sebagai salah satu jalur laut tersibuk di dunia.
Dalam konteks ini, pulau-pulau kecil di Aceh, terutama yang berada di wilayah perbatasan seperti Aceh Singkil, memegang peranan penting. Mereka adalah titik depan. Mereka adalah gerbang laut yang menjaga keutuhan wilayah dan pengaruh strategis Aceh di kawasan barat Nusantara. Kehilangan empat pulau di Singkil sama artinya dengan mundurnya benteng penjagaan Aceh. Ini bukan sekadar perubahan warna peta, ini adalah pergeseran posisi tawar dan pengaruh geopolitik yang nyata.
Empat pulau tersebut bukan daratan kosong yang tak bertuan. Di sana terdapat infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sejak lebih dari satu dekade lalu. Ada dermaga, mushala, rumah singgah, hingga tugu perbatasan bertuliskan: “Selamat Datang di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.
Ada pula dokumen kepemilikan tanah dari tahun 1965, serta peta kesepakatan batas wilayah antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disahkan pada tahun 1992, disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri saat itu. Namun semua itu seperti terhapus hanya dengan satu surat keputusan dari pusat. Di mana suara Pemerintah Aceh saat itu? Di mana peran lembaga negara yang semestinya menjaga keutuhan administratif berdasarkan sejarah dan fakta pembangunan?
Indonesia pernah kehilangan dua pulau kecil yang berada di perbatasan Kalimantan—Sipadan dan Ligitan—ke tangan Malaysia, setelah diputuskan oleh Mahkamah Internasional. Salah satu alasannya adalah karena Malaysia dinilai lebih hadir di kedua pulau itu. Mereka membangun, memberi pelayanan publik, dan mengelola wilayah tersebut secara aktif.
Dalam kasus Aceh Singkil, justru Acehlah yang selama ini hadir dan membangun. Tapi keputusannya berbalik: justru wilayah yang aktif dibangun itu dinyatakan milik provinsi tetangga. Ini adalah cermin buram dari lemahnya sistem pertahanan data spasial dan lemahnya advokasi kedaulatan wilayah. Aceh harus belajar dari masa lalu: kita tidak boleh diam. Kita harus aktif memperjuangkan kembali hak atas wilayah, dengan data, hukum, dan strategi komunikasi yang kuat.
Marwah Aceh
Pulau kecil adalah garis terluar negara. Mereka adalah tameng pertama ketika ancaman datang dari laut. Dari perompakan, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, hingga kemungkinan infiltrasi militer dari luar. Di sisi lain, pulau kecil juga menyimpan potensi besar untuk masa depan. Sebagai titik destinasi wisata, lokasi riset kelautan, bahkan sebagai sumber energi terbarukan. Menjaga pulau kecil bukan sekadar menjaga wilayah, tetapi merawat peluang masa depan.
Karena itu, perlindungan terhadap pulau-pulau kecil harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan dan pertahanan Aceh. Pemerintah Aceh perlu segera membentuk sistem pengawasan terintegrasi, termasuk teknologi satelit, drone, serta penguatan peran masyarakat lokal sebagai penjaga garda depan kedaulatan.
Apa yang terjadi di Aceh Singkil bukanlah insiden sepele. Ini adalah alarm geopolitik yang harus dibunyikan ke seluruh Aceh dan Indonesia. Hilangnya pulau bukan hanya kesalahan teknis, tapi buah dari sistem yang abai, sentralistik, dan tidak peka terhadap fakta sejarah dan sosial.
Aceh tidak boleh tinggal diam. Bukan karena semata-mata ambisi teritorial, tetapi karena kita punya tanggung jawab sejarah dan amanah otonomi khusus untuk menjaga apa yang menjadi milik kita. Kita harus bersuara. Kita harus mengangkat fakta-fakta yang selama ini terpinggirkan. Kita harus menyatukan langkah antara rakyat, pemerintah, dan dunia akademik untuk melindungi pulau-pulau kecil yang menjadi penjaga marwah kita.
Ke depan, Pemerintah Aceh harus membangun sistem informasi wilayah yang terintegrasi dan kuat.
Data spasial harus dikunci dengan sistem digital, disinkronkan dengan pusat, dan diarsipkan secara terbuka. Pulau-pulau kecil harus dicatat, dimiliki secara hukum, dan dijaga oleh tangan-tangan masyarakat. Selain itu,pendidikan geopolitik harus ditanamkan sejak dini. Masyarakat perlu sadar bahwa tanah yang mereka pijak, pulau yang mereka jaga, bukan hanya milik mereka secara lokal, tapi milik bangsa ini sebagai bagian dari kedaulatan nasional.
Hari ini, kita kehilangan empat pulau. Tapi jika kita tidak bangun dari keterkejutan ini, bukan tidak mungkin besok kita akan kehilangan lebih banyak lagi—dan saat itu, kita hanya bisa menyesal dalam diam. Pulau kecil adalah penjaga negeri. Mereka adalah simbol Aceh yang tak boleh dikecilkan nilainya. Bukan karena ukurannya, tetapi karena maknanya. Marwah bukan hanya slogan. Ia adalah tanggung jawab. Dan kita, sebagai rakyat Aceh, adalah penjaganya.